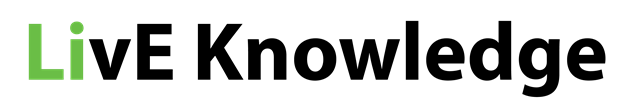LivE Knowledge – Langkah masyarakat adat Rejang di Desa Tik Sirong, desa penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Kabupaten Lebong merevitalisasi kearifan lokal terkait kebun berpola polikultur diapresiasi Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu Yansen, Ph. D.
“Aslinya, pola kebun orang Rejang memang polikultur. Artinya, apa yang mereka lakukan itu pantas diapresiasi, berupaya melestarikan kearifan lokal,” kata Yansen.
Dalam kajian ilmu ekologi, polikultur selaras dengan upaya konservasi atau upaya melindungi kestabilan ekologi. Berpola polikultur berarti menjaga kestabilan iklim mikro, memperkuat struktur tanah, menjaga kesuburan tanah, mengurangi laju limpasan air sehingga mengurangi potensi pengikisan tanah permukaan.
Pastinya, membantu pengaturan air di tanah dan menjaga keanekaragaman hayati. “Sesuai dengan sains. Polikultur berarti membangun hutan kembali,” terang Yansen.
Kebun kopi polikultur adalah langkah tepat. Sebab, kopi bukanlah tanaman monokultur. Kopi membutuhkan tanaman lain sebagai pelindung agar pertumbuhan dan produktivitasnya maksimal. Jengkol, kabau, petai, durian, lamtoro, dadap dan tumbuhan lainnya bisa menjadi pelindung, atau perpaduan sejumlah tumbuhan.
“Scientific, kopi butuh naungan. Kalau dulu, di kebun kopi orang Rejang itu biasanya ada pohon jengkol, petai dan durian.”

Pilihan masyarakat pada tanaman jengkol, kabau atau petai di kebun kopi juga tepat dari kajian ilmiah. Sebab, ketiga tumbuhan tersebut termasuk Leguminosae yang memiliki kemampuan menangkap nitrogen di udara dan mendistribusikan ke tanah melalui akar.
Sehingga, bisa menyuburkan tanah. “Semua tumbuhan butuh nitrogen, namun tidak semua mampu menyerap. Jengkol, kabau dan petai bisa melakukannya.”
Dari aspek ekonomi, pola polikultur bisa mengurangi risiko mengalami kegagalan total dari usaha yang dilakukan. Secara akumulatif pendapatan yang diperoleh bisa lebih besar dibandingkan pendapatan dari kebun monokultur. “Artinya, langkah yang dilakukan masyarakat (Desa Tik Sirong) benar dan maju. Pantas diikuti,” ujar Yansen.
Desa Tik Sirong didiami oleh masyarakat adat Rejang sejak awal 1900-an. Dulunya, daerah tersebut dikenal dengan sebutan petalangan Tik Sirong. Ditetapkan menjadi Desa Bandar Agung pada 1982, desa ini berubah nama menjadi Desa Tik Sirong pada 2008. Sebanyak 600-an kepala keluarga yang mendiami desa di hulu Daerah Aliran Sungai Air Ketahun itu.
Mayoritas penduduknya memperoleh pendapatan secara utama dari hasil berkebun kopi robusta dengan pola monokultur di tanah marga (desa) dan kawasan TNKS. Namun, pola monokultur ini mulai ditinggalkan warga, dan beralih ke polikultur. Warga melakukannya untuk memperbaiki ekonomi keluarga, sekaligus memulihkan kondisi hutan dan mengurangi laju perubahan tutupan hutan.
“Swadaya masyarakat, bukan program pemerintah,” ujar mantan Kepala Desa Tik Sirong Busroni yang dibenarkan oleh Pjs. Kepala Desa Tik Sirong, Sahrul Arufi.
Monokultur dinilai menciptakan kerentanan perekonomian. Panen yang hanya setahun sekali (Mei–Agustus) membuat penghasilan tidak cukup untuk menopang biaya hidup keluarga selama 1 tahun. Saat masa paceklik datang, Desember atau Januari, warga umumnya menjual barang, berutang atau bekerja sebagai buruh.
Kerentanan lainnya mengenai rentang waktu pengelolaan. Dampak dari degradasi lahan, produktivitas kopi menurun drastis setelah berusia 7 tahun. Masalah itu biasanya disikapi dengan membuka kebun baru dan meninggalkan kebun lama. “Kalau di kebun ada tanaman lain yang bisa dipetik yang memberikan pendapatan lumayan besar, kemungkinan untuk membuka kebun baru akan berkurang,” kata Busroni.
Pola polikultur dipilih untuk memulihkan kondisi hutan terkait temperatur lokal. Perubahan tutupan hutan di wilayah desa dan TNKS menjadi kebun kopi monokultur ikut memicu kenaikan temperatur lokal. Bukan hanya menurunkan kesuburan tanah, kenaikan temperatur juga berdampak terganggunya pertumbuhan dan perkembangan kopi, sehingga menurunkan produktivitas.
Adalah jengkol dan kabau yang menjadi tanaman campuran untuk tahap awal. Selain mudah dalam pembibitan, perawatan dan tidak mengganggu pertumbuhan kopi, masa panen buah jengkol dan kabau pada Desember-Januari, saat paceklik terjadi. Pertimbangan lainnya adalah buah tidak mudah busuk, sudah memiliki pasar dan harga jualnya relatif bagus.
Bahkan, cukup sering harga jengkol lebih mahal daripada harga daging sapi dan ayam. Menurut Busroni, langkah revitalisasi saat ini dilanjutkan dengan menanam petai, durian, dan bambu. Bambu dipilih dengan pertimbangan, selain menghindari longsor, bambu dapat digunakan untuk membuat rumah atau pondok, peralatan berkebun, perabotan rumah tangga, hingga dijual.
“Dulu, menanam bambu menjadi keharusan orang Rejang yang berkebun. Selain di sudut kebun, bambu biasanya ditanam di bagian agak curam,” ujar Busroni.
Pakar kopi dari Universitas Bengkulu, Profesor Alnopri tidak menampik sebagian besar petani kopi di Provinsi Bengkulu mengelola kebun berpola monokultur. Sehingga, jangka waktu petani memanfaatkan lahan relatif tidak lama. Setelah mengelola lahan selama 10 tahun, petani meninggalkan lahan sebagai akibat produksi kopi menurun drastis, dan membuka lahan baru.
Agroekologi Kopi untuk Mitigasi Perubahan Iklim https://t.co/chEmD7FX7w @infoMKS_ @infomks pic.twitter.com/HKaMvVHMot
— Mongabay Indonesia (@MongabayID) 15 Desember 2015
Ironisnya, daerah yang sering menjadi sasaran pembukaan lahan baru adalah kawasan hutan. “Perubahan pola pengelolaan kebun kopi yang dilakukan masyarakat bisa membantu mencegah atau meminimalisir pembukaan lahan baru, terutama di kawasan hutan yang dilindungi,” ujar Alnopri.
Dia sangat mendukung perubahan cara pandang dan praktik pengelolaan kebun kopi tersebut. Selain bisa menaikkan produksi kopi Provinsi Bengkulu yang relatif rendah (rata-rata 0,7 ton/ha), juga selaras dengan kepentingan konservasi lingkungan hidup, keanekaragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim.